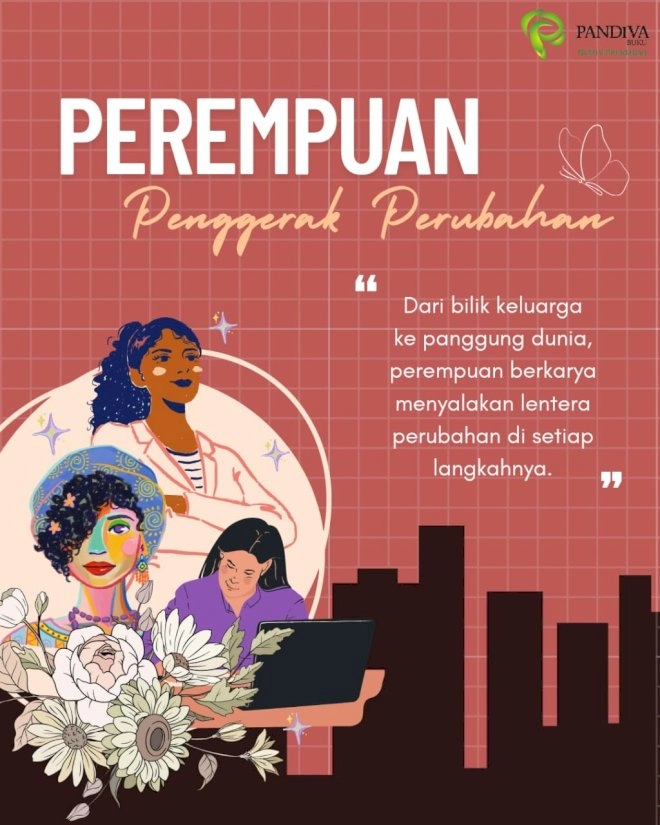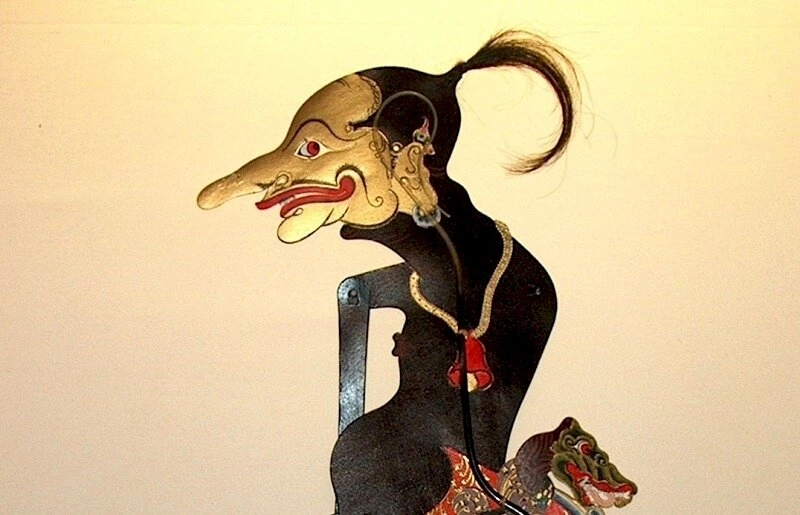Perangkap Perguruan Tinggi yang Menggiurkan Itu Bernama Hak Kelola Tambang
/ Opini
Riset hilirisasi industri tambang lebih berimplikasi strategis daripada perguruan tinggi turut dalam pengelolaan sektor usaha yang rentan merusak lingkungan itu.
Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta
Riak pewacanaan tersebut bermula dari Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI yang digelar pada Senin (20/1/2025). Forum ini membahas penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
Rapat Pleno membahas usulan tentang pemberian hak kelola tambang mineral dan batubara kepada perguruan tinggi. Usulan termaktub dalam Rancangan Undang-Undang pasal 51 A yang menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan luas WIUP mineral logam, akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah ‘B’ dan atau peningkatan akses serta layanan pendidikan bagi masyarakat.
Pemberian hak kelola WIUP kepada perguruan tinggi diusulkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) berdasarkan dokumen yang dipublikasikan pada Agustus 2024 berjudul ‘Usulan APTISI: Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045’. Dokumen mencantumkan nama Ketua APTISI 2023, Budi Djatmiko, sebagai penyusun, serta La Ode Masihu Kamaludin, seorang akademisi Universitas Halu Oleo, sebagai penyunting.
Perguruan tinggi mempunyai tugas utama menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi mempunyai dua luaran utama. Pertama, lulusan yang berkontribusi bagi masyarakat, baik sebagai tenaga profesional, akademisi, pekerja sosial, maupun pengusaha. Kedua, hasil penelitian berupa model, kebijakan, Hak Kekayaan Intelektual, paten, dan prototipe produk.
Kini, semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah berkembang menjadi entitas bisnis. Ketika Orde Baru berkuasa, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diwajibkan nirlaba, sedangkan saat ini, PTN beroperasi layaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS), karena aturan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH). PTN diwajibkan mencari pendapatan di luar anggaran pemerintah.
Konsep PTNBH sebenarnya mengharapkan PTN untuk melakukan perluasan pendapatan (income generating) yang bersumber non-mahasiswa, yaitu riset dengan hasil paten untuk industri. Sebab, PTN yang bagus mempunyai sumber daya manusia berkualitas. Namun alih-alih memperkuat riset, PTNBH justru mencari jalan mudah untuk meningkatkan tambahan pendapatan dengan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Praktik tersebut marak dilakukan PTNBH.
Situasi tersebut menjadi latar belakang pengusulan hak kelola tambang oleh perguruan tinggi. Sang pengusul, APTISI, berpendapat bahwa selama ini, PTS kalah bersaing dengan PTNBH dalam penerimaan mahasiswa, sehingga memerlukan sumber income generating lain.
Gelombang pro dan kontra pun muncul, mulai dari anggota DPR RI, pengelola perguruan tinggi, kelompok masyarakat yang berkepentingan pada pengelolaan pendidikan tinggi maupun masalah pertambangan, serta terutama, kelompok-kelompok pro-lingkungan.
Beberapa pengelola dan petinggi perguruan tinggi berpendapat berbeda. Forum Rektor, misalnya, secara umum menyetujui usulan tersebut, meskipun dengan penetapan beberapa syarat. Salah satu di antaranya, perguruan tinggi yang mendapatkan izin pengelolaan WIUP memiliki kompetensi dalam pengelolaan tambang minerba serta berkomitmen untuk menjaga lingkungan.
Kalangan yang menolak, yakni para aktivis lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berpandangan bahwa perguruan tinggi bisa terperangkap ke dalam praktik ‘bisnis hitam’ dalam pengelolaan pertambangan. Sementara beberapa pihak menilai bahwa pemberian izin pengelolaan WIUP adalah usaha pemerintah untuk membungkam kritik akademisi perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah.
Rendah Nilai Tambah
Sektor pertambangan saat ini menjadi salah satu penyumbang besar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada 2020, sektor tambang berkontribusi sebesar 6,43 persen. Tahun 2021, kontribusinya meningkat menjadi 8,97 persen. Setahun kemudian, tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan galian pada PDB melonjak menjadi 12,22 persen. Memasuki tahun 2023, angkanya turun sedikit menjadi 10,52 persen.
Pada sisi lain, industri pengolahan atau manufaktur justru mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB Indonesia. Tahun 2020, industri ini berkontribusi 19,87 persen pada PDB, lalu turun menjadi 19,24 persen pada tahun 2021, kemudian kembali turun menjadi 18,34 persen pada tahun 2022, dan tahun 2023, sedikit naik menjadi 18,67 persen.
Peningkatan kontribusi sektor pertambangan juga ditunjukkan dari data surplus ekspor nikel pada tahun 2022 yang mencapai US$ 291,88 miliar atau Rp4.524 triliun. Dalam jangka pendek, hal ini tentu menggembirakan, tetapi dalam rentang jangka panjang, perekonomian Indonesia dinilai mundur ke zaman awal Orde Baru, saat PDB disokong, terutama dari sektor primer. Kondisi yang dapat memicu kerentanan dalam stabilitas ekonomi. Sebab, ketergantungan pada komoditas mentah berarti telah siap dengan fluktuasi harga komoditas.
Kontribusi sektor pertambangan dan galian yang terus meningkat ternyata tidak dibersamai dengan nilai tambah, lantaran hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah. Hal inilah yang menyebabkan sektor pertambangan dan galian begitu tergantung pada fluktuasi harga komoditas global.
Pemerintah sebenarnya berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan dengan mendorong hilirisasi sektor pertambangan dan galian. Hilirisasi pada tahap pertama yakni membangun smelter atau pabrik pengolahan logam dan mineral untuk mendapatkan logam dengan kandungan kemurnian yang tinggi, sehingga harganya juga lebih tinggi di pasar global.
Pemerintah pun membangun serta mengundang investor untuk mendirikan smelter nikel dan timah yang saat ini menjadi primadona pertambangan logam dan mineral. Pembangunan smelter diharapkan meningkatkan nilai tambah ekonomi sektor pertambangan dan galian, karena adanya penyerapan tenaga kerja serta penggunaan teknologi pemurnian logam.
Idealnya pula, industri pengolahan yang dibangun di Indonesia sebagai turunan dari produk logam, misalnya industri baterai untuk kendaraan listrik, industri otomotif dan komponen otomotif, industri perkapalan, serta berbagai industri pengolahan berbahan baku logam. Dalam konteks inilah, peran perguruan tinggi sangat strategis.
Riset Demi Nilai Tambah
Kian hari, pengelolaan perguruan tinggi memang jauh lebih rumit, karena perubahan tuntutan stakeholders. Sebagian besar perguruan tinggi di dunia masih berpola teaching university. Artinya, masih mengandalkan penerimaan dari iuran mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi dunia yang masuk Ivy League mendapatkan banyak dana hibah dari donatur, yaitu alumni dan berbagai Yayasan filantropi untuk membiayai kegiatan akademik mereka. Perguruan tinggi lain dengan QS World University Ranking dan Times Higher Education World University Rankings (THE) tinggi di dunia mendapatkan pendapatan tambahan dari paten yang mereka miliki.
Berdasarkan data dari Departemen Riset Statista, pada tahun 2022, University of California di Amerika Serikat dinobatkan sebagai perguruan tinggi dengan pengajuan paten terbanyak di dunia, yakni 522 paten. Pada peringkat kedua dan ketiga, tercatat perguruan tinggi dari Tiongkok, yaitu Universitas Zhejiang dan Universitas Suzhou. Tetangga dekat Indonesia, National University of Singapore (NUS), berhasil menduduki peringkat ke-13. Perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti inilah yang layak menyebut dirinya sebagai research university. Sementara itu, perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia, baik PTN maupun PTS, masih mengandalkan pendapatan mereka dari iuran mahasiswa.
Dalam konteks pengelolaan tambang, perguruan tinggi dapat menyediakan teknologi tepat guna hasil dari penelitian. Tujuannya, meningkatkan nilai tambah ekonomi. Teknologi ini diharapkan bisa dimanfaatkan industri pengolahan sebagai turunan komoditas tambang. Selanjutnya, perguruan tinggi akan mendapatkan penghasilan dari paten hasil riset hilirisasi di bidang pertambangan.
Pertanyaannya, mampukah perguruan tinggi Indonesia menjawab tantangan itu? Pengelolaan WIUP mungkin bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan berkurangnya pendapatan PTS yang kalah bersaing dengan PTNBH dalam mendapatkan mahasiswa. Namun, dalam jangka panjang, PTS dan PTN bisa terjebak dalam bisnis makelar komoditas pertambangan yang merusak lingkungan.
Editor: Rahma Frida