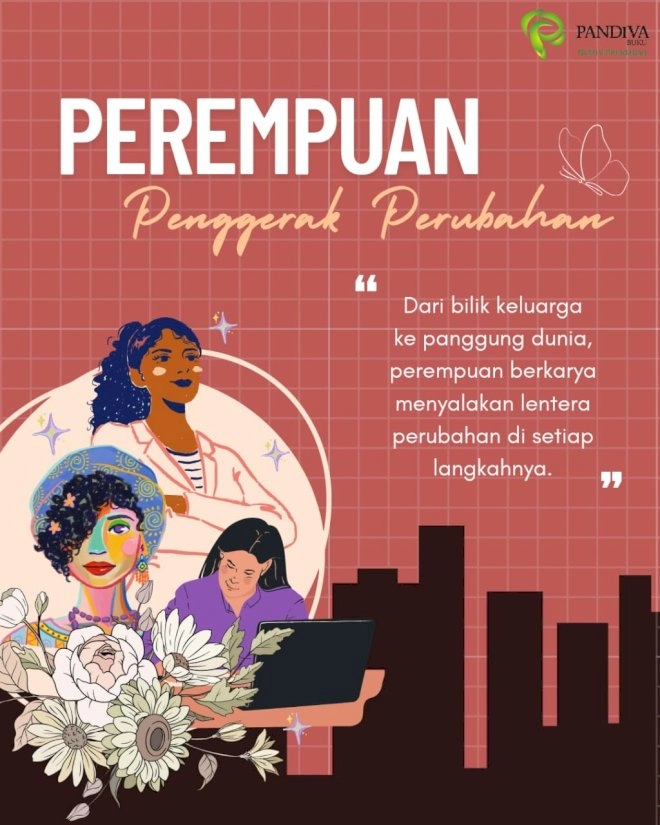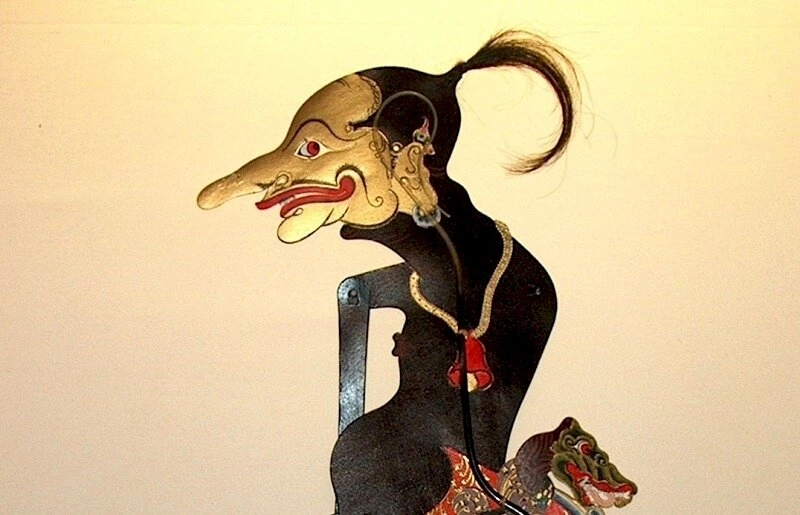Pendataan Disabilitas, antara Dinamika, Stigma, dan Kesetaraan
/ Opini
Pendekatan dan definisi disabilitas belum mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi aktivitas seseorang. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata.
Agus Sulistyo
Anggota Bawaslu Kota Surakarta.
Penulis buku Solo Ramah Demokrasi.
Jalan terjal pendataan penyandang disabilitas di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pendataan dimulai sejak Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 1995. Hasilnya menunjukkan angka 1,7 juta penyandang disabilitas atau hanya 0,9 persen dari total penduduk Indonesia yang kala itu berjumlah 199,9 juta jiwa.
Angka tersebut terbilang rendah, karena pendekatan yang digunakan masih bersifat medis. Pada awalnya, definisi disabilitas hanya melihat dari aspek fisik, yaitu secara medis dari aspek kehilangan fungsi anatomi atau fisiologi. Pendekatan dan definisi disabilitas ini belum mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi aktivitas seseorang. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata.
Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran paradigma. Disabilitas bukan semata kondisi tubuh, namun juga dapat diakibatkan oleh interaksi antara individu dan lingkungan. Perubahan pendekatan tersebut membawa implikasi signifikan. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta orang atau sekitar 8,2 persen dari total penduduk 281,2 juta jiwa (BPS tahun 2023).
Lonjakan tajam itu bukan semata karena meningkatnya jumlah penyandang disabilitas, melainkan karena perluasan definisi yang lebih inklusif dan berfokus pada hambatan aktivitas sehari-hari. Bukan sekadar kelainan fisik sebagaimana definisi sebelumnya. Kenaikan lantas membuka mata bahwa sekian lama banyak kelompok disabilitas tersembunyi di balik data yang tidak lengkap.
Dengan data yang lebih komprehensif, harapannya kebijakan pun dapat diarahkan secara lebih efektif, semisal untuk akses pendidikan inklusif, layanan informasi inklusif, termasuk literasi digital, demokrasi dan pendidikan politik akses, kesempatan kerja, maupun layanan kesehatan.
Namun demikian, dalam konteks yang lain, perubahan jumlah penyandang disabilitas juga menimbulkan tantangan baru. Pemerintah daerah, contohnya, masih menghadapi keterbatasan SDM, infrastruktur, dan regulasi yang implementatif. Harapannya, sajian data disabilitas juga tidak hanya menjadi angka pemanis yang selanjutnya diklaim sebagai program inklusif.
Dilema Sosial dalam Pendataan Berwujud Stigma
Hal ihwal pendataan disabilitas di Indonesia bukan sekadar urusan statistik atau administratif. Namun demikian, pendataan lebih dari urusan administratif, yaitu persoalan kemanusiaan dan kesetaraan. Ia berhadapan langsung dengan realitas sosial yang masih sarat stigma terhadap kaum disabilitas. Permasalahan yang muncul tidak berhenti pada teknis administratif, tetapi paradigma yang berkembang di lingkungan keluarga dan sosial masyarakat.
Sebagian masyarakat masih memandang disabilitas dengan stigma negatif, seperti lemah, tidak produktif, bahkan menjadi hanya menjadi ‘beban’. Dalam konteks seperti itu, tidak sedikit penyandang disabilitas atau keluarganya enggan didata, karena takut dicap berbeda dengan masyarakat pada umumnya.
Selama stigma masih melekat, angka disabilitas akan selalu mengalami bias. Oleh karena itu, hal yang dibutuhkan bukan hanya program pendataan yang komprehensif, tetapi juga program literasi secara holistik dengan pembudayaan inklusivitas.
Ironisnya, tidak jarang pendataan yang substansinya bertujuan memperjuangkan hak dan layanan disabilitas justru menimbulkan resistensi sosial. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan melakukan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif di masyarakat.
Selain itu, pekerjaan rumah pemerintah dan seluruh stakeholder adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat terhadap isu disabilitas yang juga dapat dilakukan dengan pendekatan literasi publik secara berkelanjutan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap isu disabilitas, semakin kecil kemungkinan stigma negatif itu bertahan.
Manunggalnya Pendataan, Literasi, dan Regulasi
Pendataan, literasi, dan regulasi merupakan tiga pilar yang tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya membentuk satu ekosistem yang saling memperkuat. Pendataan memberikan dasar empiris, literasi mengubah cara pandang publik, dan regulasi menjadi dasar yang menjembatani keduanya menjadi tindakan nyata.
Pendataan yang berhasil bukan hanya berhenti pada laporan administrasi dan angka statistik. Namun, sejauh mana negara mampu menyeimbangkan akurasi data dengan sensitivitas kemanusiaan. Regulasi harus terimplementasi dalam wajah kebijakan publik yang inklusif dan mampu membangun sikap optimisme masyarakat. Karena, kebijakan inklusi membutuhkan empati, bukan justru menyemai bibit-bibit resistensi.
Dalam sisi yang lain, data empiris tanpa literasi juga hanya akan melahirkan angka tanpa makna. Sebaliknya, literasi tanpa regulasi hanya akan menjadi wacana dan dianggap pepesan kosong karena tidak menemukan substansinya.
Sebagai gambaran bahwa gerakan literasi tidak bisa datang begitu saja. Contoh buku-buku seperti Difabel dalam Kemegahan Pembangunan Kota karya Ringgana Wandy Wiguna (Pandiva, 2022) menjadi khazanah upaya memperluas kesadaran publik. Melalui salah satu karya semacam itu, isu disabilitas bukan lagi menjadi isu sektarian tetapi menjadi isu di ranah publik yang menjdi diskursus sosial-politik.
Dengan begitu, keberhasilan pendataan disabilitas bukan hanya diukur dari jumlah data disabilitas yang terkumpul, tetapi sejauh mana data mampu mewujudkan regulasi yang inklusif. Akhirnya akan dapat mengubah perilaku sosial yang menganggap disabilitas tidak lagi sebagai golongan ‘kelas dua’ dan ‘perbedaan’, melainkan sebagai bagian dari keragaman manusia.
Validitas data dalam pendataan penyandang disabilitas menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah tepat guna, tepat sasaran, dan berkeadilan. Di atas kertas, pendataan tampak rasional, tetapi di lapangan ia sering kali menyinggung hal yang amat personal, yaitu identitas dan penerimaan sosial.
Tampaknya terlihat sederhana, namun proses pendataan tidak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah perlu menggandeng lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas narasi positif tentang disabilitas secara berkelanjutan.
Selain itu, kampanye membangun penyadaran publik, pelatihan sensitif disabilitas, serta keterlibatan komunitas disabilitas dalam penyusunan regulasi merupakan langkah strategis menuju masyarakat tanpa stigma.
Penting pula bagi pemerintah untuk membangun sistem pendataan yang terintegrasi lintas lembaga. Data dari BPS, Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan, hingga KPU perlu disinergikan agar data tidak terjadi tumpang tindih informasi. Jika data menjadi bahan baku regulasi maka regulasi menjadi bahan dasar menuju kesetaraan (kebijakan). Oleh karenanya, pendataan disabilitas dan regulasi menjadi rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
Menembus Hak Dasar dan Hak Politik
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan adanya hak kesetaraan yang mendorong pendataan berbasis hak asasi manusia (HAM). Paradigma pun mulai bergeser dari sekedar administratif, selanjutnya bertransformasi menjadi simbol pengakuan eksistensi dan pengakuan hak.
Termasuk di dalamnya hak atas identitas Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). KPD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan.
Undang-undang tersebut juga menjadi jembatan menuju integrasi data ke dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar penyandang disabilitas benar-benar diakui secara resmi dan setara sebagai warga negara. Sementara KTP menjadi instrumen persyaratan, apakah seseorang mempunyai hak politik atau belum pada mekanisme pendaftaran pemilih oleh KPU.
Secara regulatif dalam upaya memperkuat hak politik penyandang disabilitas dari Pemilu ke Pemilu terlihat semakin jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak untuk dipilih dan memilih. Pada Pemilu 2024 yang lalu tercatat 1,1 juta pemilih disabilitas atau sekitar 0,54 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 204,8 juta orang. Angka ini menegaskan bahwa kaum disabilitas merupakan segmen penting dalam demokrasi Indonesia.
Penyelenggara pemilu telah berupaya memastikan inklusivitas melalui berbagai regulasi, misalnya penentuan lokasi TPS yang mudah diakses, penyediaan surat suara braille, alat bantu coblos, hingga pendampingan bagi pemilih disabilitas. KPU juga menetapkan standar aksesibilitas, seperti pintu masuk minimal 90 cm untuk kursi roda, meja dengan tinggi maksimal 75 cm, serta area tanpa tangga atau parit.
Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tidaklah selalu berjalan ideal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Banyak fenomena yang terjadi, TPS belum sepenuhnya ramah disabilitas. Hasil pemantauan Sigab Indonesia dan Formasi Disabilitas menemukan sejumlah TPS di daerah masih belum memiliki akses kursi roda, petugas belum terlatih berkomunikasi dengan pemilih tunarungu, serta belum tersedia surat suara untuk disabilitas netra dalam huruf braille di beberapa lokasi.
Minimnya pendampingan, masih terbatasnya alat bantu di TPS, dan sosialisasi yang belum menyentuh ragam disabilitas intelektual secara efektif menjadi persoalan klasik dari Pemilu ke Pemilu. Pemahaman yang kurang tentang disabilitas oleh penyelenggara ad hoc juga menjadi elemen penting dalam representasi dan partisipasi disabilitas dalam kontestasi elektoral.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan pemilih disabilitas belum sepenuhnya terhubung dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan. Padahal, hak politik adalah hak fundamental dari kesetaraan warga negara. Bila akses terhadap hak pilih masih terhalang maka makna demokrasi inklusif belum sepenuhnya terwujud. Allahu a’lam bi showab.
Editor: Astama Izqi Winata