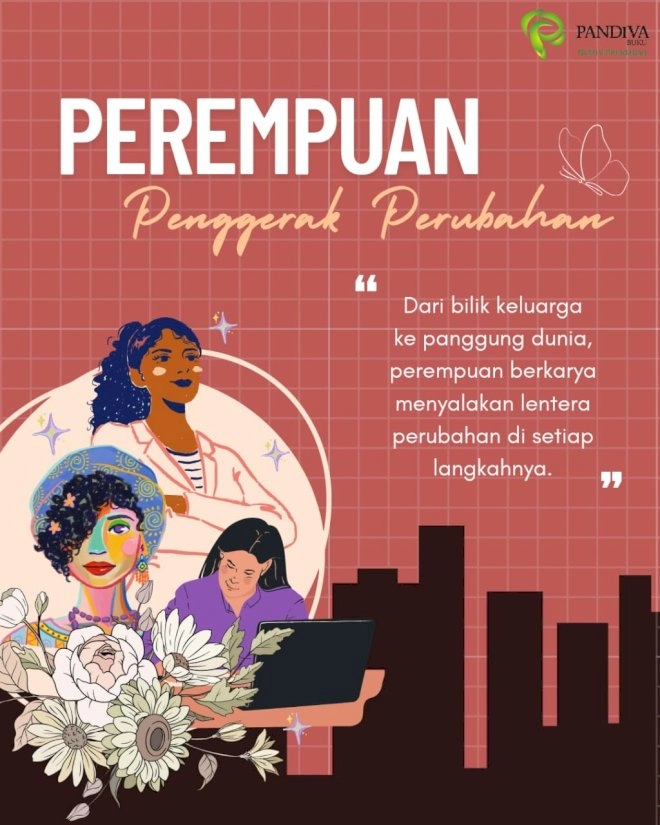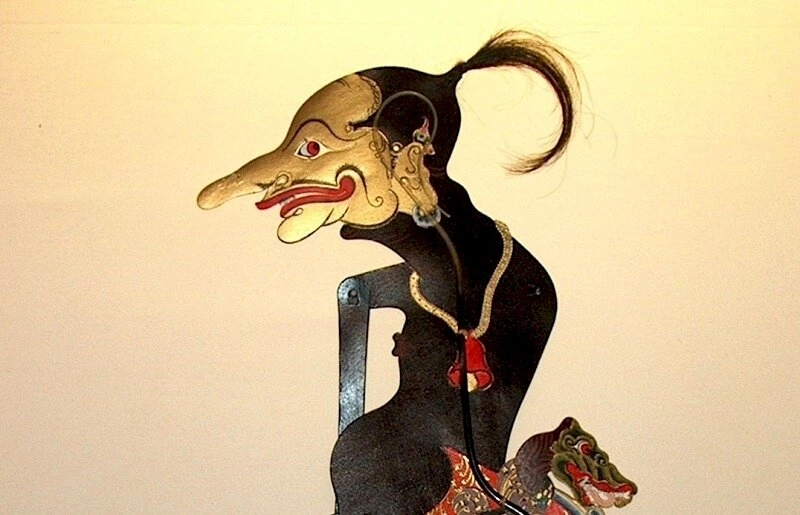Menjadi Kelas Menengah Nasionalis
/ Opini
Konsolidasi Kelas Menengah menjadi masuk akal lantaran secara jumlah begitu sedikit dan tidak menarik secara elektoral.
Arif Giyanto
Chairman Pandiva dan Penulis buku Kelas Menengah Progresif
Jumat (7/2/2025) dini hari, saya dibangunkan istri saya. Karena masih dalam bulan Sya’ban, saya pikir, saya dibangunkan untuk makan sahur. Belum sepenuhnya sadar, saya diberi tahu bahwa gas untuk memasak, habis. Dini hari yang tiba-tiba terasa darurat.
Saya tinggal di Kalasan, Sleman. Pada jam-jam tersebut, mendapatkan gas bukanlah hal mudah. Praktis, saya hanya berharap pada warung Madura yang memang buka 24 jam. Bila pun tersedia, mereka umumnya menyediakan gas 3 kilogram atau lazim disebut ‘gas melon’.
Di rumah, ada tiga tabung gas. Satu gas 3 kilogram dan dua gas 12 kilogram. Gas 3 kilogram ini ‘bawaan’ dari 2009, atau dua tahun sejak Pertamina memperkenalkan elpiji bagi kalangan berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih terjangkau. Ketika itu, elpiji dan kompor gas mulai masuk ke desa-desa. Disebut bawaan, karena berlatar historis. Banyak kenangannya. Jadi, gas melon tersebut akhirnya tetap dipertahankan di dapur.
Hidup terus berubah. Dalam perjalanan rumah tangga saya, gas melon bersejarah ini mulai berteman gas 12 kilogram bahkan dua tabung sekaligus. Bila keuangan rumah sedang bagus, gas melon tidak pernah diisi ulang. Sebab, dua tabung gas lain secara bergantian diperankan optimal. Namun, bila pendapatan sedang fluktuatif, gas melon diisi ulang plus satu tabung gas 12 kilogram. Sementara gas 12 kilogram yang satunya, dipensiunkan berkala.
Dini hari darurat lalu, saya lantas berkeliling, dengan membawa tabung gas melon kosong. Saya mendatangi warung-warung Madura. Entah berapa lapak serupa yang saya datangi. Hingga azan Subuh berkumandang, tak satu pun lapak yang menyediakan gas melon. Hampir semua bilang, gas melon sedang susah didapat.
Rupanya, per 1 Februari 2025, pemerintah melarang pengecer gas melon untuk menjual elpiji kepada masyarakat. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. Dengan masygul, saya kembali ke rumah, tanpa hasil. Solusinya, saya harus rela menunggu pagi agar bisa mengisi ulang gas 12 kilogram dari pengecer langganan.
Sepanjang jalan, saya berpikir, mungkin bila dua tabung gas 12 kilogram yang ada di rumah diisi bergantian dengan tertib dan tepat waktu, kejadian darurat seperti ini tidak akan terjadi. Tapi hidup tak ada seharusnya. Setidaknya, saya kemudian dapat turut merasakan, susahnya mendapatkan elpiji melon yang populer itu.
Apabila ditengarai lebih dalam, ketidaksiapan saya dalam memitigasi penggunaan gas merupakan salah satu implikasi ketidakpastian usaha saya dalam beberapa tahun terakhir. Saya survive dengan satu elpiji 12 kilogram dan 3 kilogram yang biasanya dipesan bersamaan. Secara sosial, saya menilai diri saya sendiri sebagai Kelas Menengah yang tengah berusaha keras untuk tidak tergantung pada gas melon.
Dengan begitu, saya pikir, situasi dapur akan aman. Tapi ternyata, tidak selalu. Pada saat subsidi secara bertahap dikurangi bahkan dihapuskan, pilihan survive saya tidak lagi dapat memanfaatkan elpiji 12 kilogram sebagai representasi Kelas Menengah dan gas melon bagi kalangan tidak mampu dalam satu waktu. Saya seperti dipaksa memilih, tetap termasuk dalam Kelas Menengah dengan konsekuensi konsumsi elpiji 12 kilogram saja, atau legawa sebagai Kelas Bawah yang berhak atas subsidi gas melon.
Secara taktis dan realistis, tentu saja tidak banyak orang yang berlebihan merespons pengelompokan kelas-kelas sosial. Bila mampu, elpiji 12 kilogram pilihannya. Karena, penggunaannya oleh dapur rumah tangga keluarga kecil biasa, rata-rata dapat mencapai dua bulan. Hal itu memungkinkan efisiensi, terutama waktu. Tidak sering gonta-ganti tabung elpiji. Belum lagi karet gas melon yang seringnya bisa bikin depresi singkat saat pemasangan. Sebaliknya, bila sedang tak mampu, mengkonsumsi gas melon pun tak apa, meski harus disubsidi negara.
Fenomena ‘serba-salah’ Kelas Menengah seperti ini, sebenarnya bukan hal baru. Hidup yang terasa kental anomalinya harus menjadi hal lumrah, lantaran keadaannya memang begitu. Dalam satu waktu, Kelas Menengah bisa saja berembuk tentang mulianya pemberdayaan rakyat dan dengan sadar bahwa ia juga masih perlu diberdayakan. Kali lain, mereka membahas potensi bisnis start-up bernilai triliunan bersama para kandidat investor, toh saat pulang, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tabungannya tak cukup untuk hidup hingga minggu depan.
Bermobil bagus, tapi turut antrean Pertalite. Telepon genggam yang bermerek, tapi lebih suka Wi-Fi gratisan. Punya banyak kartu bank, tapi tak satu pun yang dapat diandalkan. Belum lagi, tak bisa ambil rumah bersubsidi, karena dinilai tidak layak. Masih banyak lagi. Tapi begitulah Kelas Menengah bertahan hidup.
Konsolidasi Nasional
Berdasar pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi Kelas Menengah sebagai masyarakat dengan pengeluaran berkisar Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan pada 2024. Jumlah mereka hanya 17,13 persen dari total penduduk Indonesia atau sebanyak 47,85 juta orang. Berdasarkan jumlah, tak jauh berbeda dengan jumlah penduduk Jawa Barat, yakni 50,36 juta orang.
Di sisi lain, total jumlah orang yang bekerja di sektor formal per Agustus 2024 sebanyak 60,82 juta jiwa. Sejumlah 4.758.730 orang di sektor formal ini berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peran ASN yang cenderung pada kinerja penyelenggaraan pemerintah berbeda dengan kegiatan perekonomian yang berorientasi profit.
Merujuk pada kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) terendah pada tahun 2024, yakni Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp 2.038.005, atau hampir sama dengan pengeluaran terendah Kelas Menengah, ternyata ada perbedaan jumlah antara jumlah Kelas Menengah yakni 47,85 juta dengan penduduk yang bekerja di sektor formal yaitu 60,82 juta.
Bila kebijakan UMK diterapkan dengan baik di sektor formal, meski di angka terendah sekalipun, akan dapat mendongkrak jumlah Kelas Menengah, setidaknya sama dengan jumlah orang yang bekerja di sektor formal. Artinya, sektor formal yang digadang-gadang paling potensial dalam mengembang-biakkan populasi Kelas Menengah terbukti tidak selalu seperti yang diharapkan.
Bisa juga ditafsirkan, kebijakan UMK yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, belum juga berhasil. Sektor formal pada kenyataannya tertekan, akibat situasi perekonomian dan daya beli masyarakat yang belum sebanding. Walhasil, bila tidak terseok-seok bertahan, sektor formal biasanya berkeputusan untuk tidak lagi beroperasi.
Dari sini, tampak jelas bahwa eksistensi Kelas Menengah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terutama di sektor ekonomi formal. Sementara sektor ekonomi formal tak luput dari pengaruh situasi perekonomian nasional. Selanjutnya, situasi perekonomian nasional begitu ditentukan oleh situasi politik dan kepemimpinan nasional.
Runtutan pembahasan ini bermuara pada urgensi kiprah Kelas Menengah dalam payung konsolidasi nasional. Sebuah rekomendasi yang mulai terdengar tidak realistis dan mengada-ada. Mengapa konsolidasi? Jumlah Kelas Menengah yang sedikit tidak menarik secara elektoral. Kebijakan populis seperti subsidi, bantuan sosial, atau serupa itu, sulit menyentuh Kelas Menengah. Pemerintah juga cenderung berkolaborasi dengan Kelas Atas, lantaran sumber daya yang mereka miliki.
Konsolidasi nasional dapat bermula dari penguatan nasionalisme kalangan Kelas Menengah. Tanpa itu, mereka akan bersikap oportunis-pragmatis, atau cenderung individualis, dan mengabaikan jalinan kekuatan antar-lini yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Menjadi nasionalis dalam kondisi serba-terbatas tentu saja tak mudah. Namun, bertahan dengan keapa-adaan kekuatan yang ada pada masing-masing, jelas tak menjamin perbaikan keadaan Kelas Menengah.
Dengan menjadi nasionalis, Kelas Menengah tak perlu khawatir dengan tesis Russell Smith dalam bukunya berjudul Stop Middle Class Genocide (2014) yang menyebutkan bahwa Kelas Menengah sering kali tereliminasi sebagai kekuatan sosial independen, lantaran menjadi korban perubahan struktural dalam ekonomi dan politik. Kekuatan Kelas Menengah nasionalis pada praktiknya dapat bernegosiasi dengan pasar dunia lebih objektif, karena didukung oleh bermacam kekuatan produksi dalam negeri yang saling melengkapi.
Mengutip Joan Robinson, seorang Guru Besar Ekonomi Universitas Cambridge yang disetujui Bung Hatta, The very nature of economics is rooted in nationalism. Identitas kebangsaan pada akhirnya relevan di Indonesia, termasuk dalam sekup ekonomi, karena negeri ini lahir oleh gelora cinta Tanah Air yang tak lekang zaman.
Editor: Astama Izqi Winata