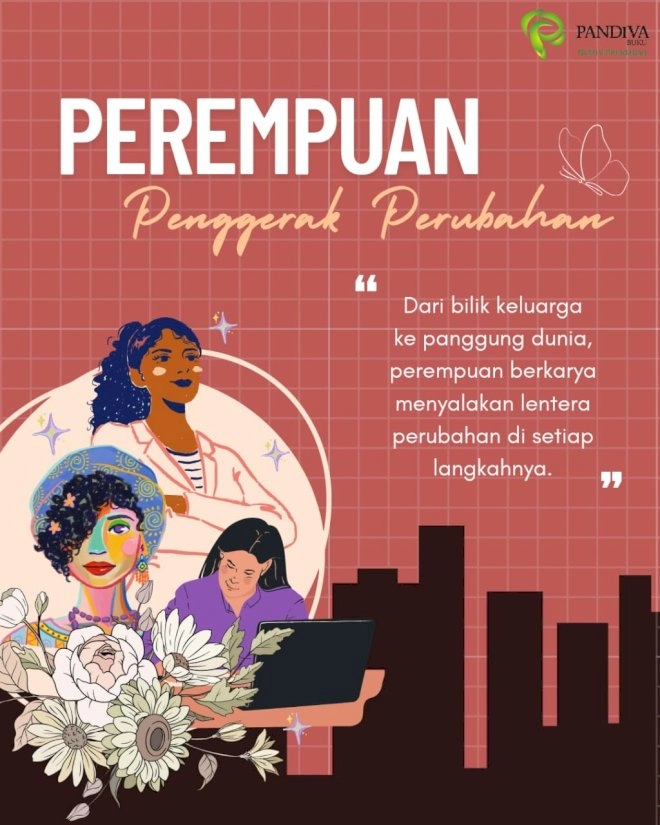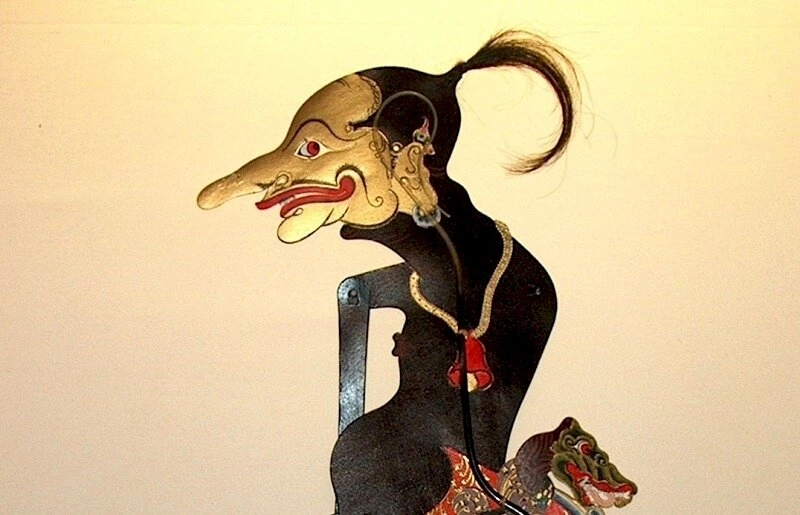Jalan Terjal Kesetaraan Disabilitas
/ Opini
Kesetaraan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, salah satunya diukur dari hak pilih.
Agus Sulistyo
Anggota Bawaslu Kota Surakarta.
Penulis buku Solo Ramah Demokrasi.
Pada Rabu, 1 Februari 1961, Presiden Soekarno menerima Aek Natas Siregar dan Mumuh Wiraatmadja. Keduanya ialah Ketua dan Penulis Serikat Kaum Tuli-Bisu (Sekatubi). Mereka berkeputusan untuk menghadap Bung Karno, setelah sekian lama berjuang demi kesetaraan kaum tuli dan bisu di ranah pendidikan dan kesempatan kerja, belum tampak tanda-tanda keberhasilan.
Sebenarnya, Sekatubi memiliki dasar hukum kuat. Demi keadilan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 pasal 7 ayat 5 telah beramanat untuk memelihara dan mendidik ‘orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya’. Mereka terdiri dari orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel (disebut juga imbecile yang berarti pandir), atau lainnya. Dengan pemeliharaan dan pendidikan, mereka berkesempatan hidup selayaknya manusia.
Dicantumkan dalam Pasal 22 undang-undang tersebut bahwa di sekolah tingkat rendah, warga negara yang cacat tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran sesuai dengan prinsip kewajiban belajar, sebagai kompensasi penderitaan mereka.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 bertumpu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pada pasal 7 ayat 5, termaktub amanat penting tentang maksud dari pendidikan dan pengajaran luar biasa, yakni memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan baik jasmani dan rohaninya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir-batin yang layak.
Namun, lantaran Republik belum benar-benar prima, implementasi perundangan-perundangan itu masih jauh panggang dari api. Negara disibukkan dengan perkara-perkara strategis lain, terutama usai pengakuan kedaulatan, setelah berjuang fisik dan diplomasi, begitu lamanya.
Menerima Siregar dan Mumuh, Bung Karno lantas memberi dukungan penting. Bahkan Sang Proklamator mendoakan upaya mulia tersebut dalam secarik kertas, “Mudah-mudahan usaha Siregar dan Mumuh dapat tercapai, sampai semua anak-anak bisu-tuli dapat perhatian dari pemerintah. Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi.”
Siregar seorang tuna rungu. Pun demikian dengan Mumuh. Bung Karno perlu menuliskan doanya pada secarik kertas, karena dengan begitu, dapat dibaca oleh Siregar dan Mumuh. Gaya bicara berapi-api Presiden Soekarno yang selama itu dikenal mendunia, tidak dapat diketahui keduanya. Namun, tujuan mereka bersua Sang Presiden untuk mendapat dukungan, telah tercapai.
Momentum tersebut menjadi pembicaraan hangat berbagai pihak, setelahnya. Namun, tahun berlalu, hingga presiden berganti, tak tercatat sejarah signifikan perihal kehadiran negara atas disabilitas. Baru pada 28 Februari 1997, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Semasa rentang waktu itu pula, perdebatan istilah mengemuka kuat. Sebagian kalangan, memilih istilah ‘difabel’ daripada ‘penyandang cacat’ atau ‘disabilitas’. Difabel (difable) atau different ability dapat diartikan seseorang yang memiliki kemampuan berbeda. Sementara penyandang cacat terkesan tak normal, dan disabilitas dimaknai keterbatan atau ketidakmampuan.
Selang lebih dari satu dekade, terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Istilah ‘disabilitas’ pun digunakan secara resmi di Indonesia. Konvensi yang disahkan tahun 2006 tersebut bertujuan memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak serta kebebasan dasar bagi semua penyandang disabilitas. Selain itu, diwajibkan untuk menghormati martabat mereka.
Penggunaan istilah disabilitas semakin menguat ketika disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Sejak itu, hingga kini, publik lebih familier dengan sebutan disabilitas, ketimbang difabel, apalagi penyandang cacat. Meski demi inklusivitas, sebagian kalangan juga masih setia dengan sebutan difabel.
Hak Pilih Penyandang Disabilitas
Kesetaraan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia, salah satunya diukur dari hak pilih. UU 8/2016 dengan tegas mengamanatkan hak politik mereka. Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa mereka berhak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Mereka juga berhak menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan.
Penyandang disabilitas juga dijamin haknya untuk memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Selain itu, membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik.
Perundangan menjamin hak kaum disabilitas untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Tidak lupa, hak untuk berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilihan Umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya, serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Wali Kota, dan Pemilihan Kepala Desa atau nama lain. Kaum disabilitas pun berhak atas pendidikan politik.
Pemerintah memperkuat hak pilih penyandang disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 5 perundangan ini menyebut penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.
Untuk menakar seberapa implementatif perundangan-perundangan tersebut, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 dapat menjadi ukurannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantas menjamin aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didesain ramah disabilitas, termasuk akses bagi pengguna kursi roda.
Penyandang disabilitas diperbolehkan bersama pendamping serta wajib mengisi Formulir C3. KPU juga menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti alat bantu bagi tunanetra. Bukan hanya itu, sosialisasi dan edukasi sosialisasi dan pendidikan politik ditempuh pula oleh KPU agar para penyandang disabilitas memahami proses pemungutan suara.
Bagi penyelenggara Pemilu, dari satu momentum pemilihan ke momentum pemilihan selanjutnya, selalu menyisakan evaluasi penting seputar optimalisasi implementasi undang-undang tentang hak pilih para penyandang disabilitas. Sebagian persoalan dapat diatasi, sedangkan lebih banyak persoalan yang masih perlu penanganan ekstra.
Setiap penyelenggara Pemilu bisa jadi juga memiliki cara, inovasi, dan kreativitas untuk itu. Semuanya didasarkan pada pendekatan yang berbeda-beda di setiap daerah. Pemenuhan hak pilih kaum disabilitas sangat dipengaruhi pula oleh sumber daya yang ada. Titik vitalnya, ada pada sumber daya manusia yang paham akan hak pilih kaum disabilitas berdasarkan undang-undang.
Seberat apa pun implementasi regulasi hak pilih penyandang disabilitas, optimisme tetap harus ada. Dengan berbagi pengalaman antar-pemangku kepentingan dapat mengurai benang kusutnya. Kian hari, para peneliti yang tak jemu menggelar studi tentang hak pilih para penyandang disabilitas terus bermunculan. Sebuah bukti kepedulian setiap kita untuk benar-benar merealisasikan hak pilih mereka sebagai bukti adanya kesetaraan.
Editor: Arif Giyanto