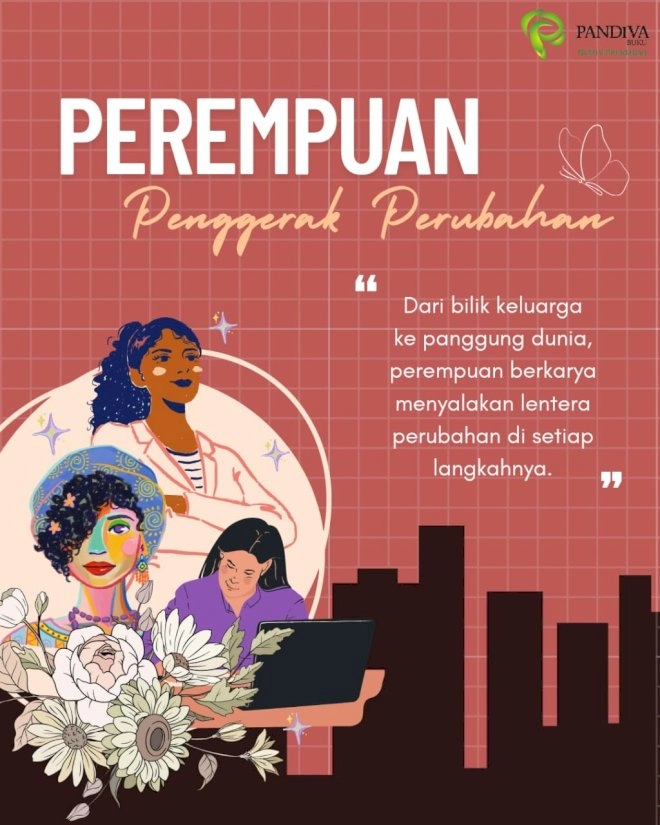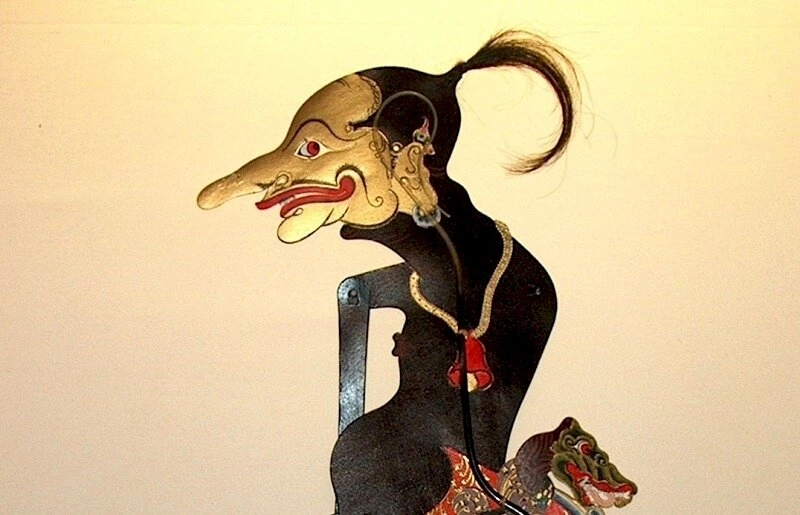HMI-PMII tentang ‘Tumbuh dari Bawah’
/ Opini
HMI dan PMII adalah potret dua jalan dengan satu tujuan, yakni mencerdaskan bangsa.
Nyuwardi
Pengurus Besar HMI 2002-2004. Alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS). Komisioner KPU Kabupaten Boyolali.
Ahad (13/7/2025) lalu menjadi momentum berharga bagi perjalanan republik ini. Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) periode 2025-2030 dikukuhkan. Ribuan alumnus organisasi kemahasiswaan yang lahir pada 17 April 1960 tersebut tercatat berkiprah di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengukuhan PB IKA PMII kali ini mendapatkan sorotan luas khalayak nasional. Bukan hanya tentang rasa bangga atas eksistensi PMII yang terawat baik, tapi juga tentang pernyataan strategis Sang Ketua Majelis Pembina Nasional (Mabinas) PB PMII, Muhaimin Iskandar. Saat memberikan sambutan, secara tak terduga Cak Imin berseloroh, “Yang tumbuh dari bawah adalah PMII, bukan HMI.”
Nama HMI dimunculkan Cak Imin dalam gelaran akbar itu. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan oleh Lafran Pane dan kawan-kawan pada 5 Februari 1947, atau 13 tahun sebelum kelahiran PMII. HMI hadir merespons kebutuhan akan organisasi mahasiswa Islam yang tidak hanya taat pada agama, tapi juga aktif dalam urusan kebangsaan. Bermula dari Jogja, eksistensi HMI meluas hingga ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri.
Dalam perkembangan dinamikanya, HMI lantas dikenal akan pemahamannya tentang Islam inklusif, intelektualisme Islam, dan modernisme Islam. Dengan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang disusun oleh tokoh pembaru Islam, Nurcholish Madjid atau akrab disapa Cak Nur, HMI menjadi pelopor perpaduan semangat keislaman dengan pemikiran rasional dan modern.
Salah satu referensi yang bisa diangkat, yakni buku karya Agussalim Sitompul berjudul Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI 1947-1997. Buku terbitan Logos Wacana Jakarta tahun 2002 ini menjabarkan kemanunggalan HMI dengan republik dalam kacamata intelektualisme.
HMI membentuk kader dengan pendekatan teoretis dan intelektual. Tradisi debat, diskusi ilmiah, penulisan, dan analisis filsafat menjadi makanan sehari-hari. Tak heran bila banyak tokoh nasional, akademisi, dan pemikir besar lahir dari rahim HMI, seperti Anies Baswedan, Akbar Tanjung, dan Yusril Ihza Mahendra.
Sementara itu, dalam rentang masanya, PMII dikenal sebagai gerakan sosial mahasiswa Islam yang ‘membumi’. PMII lahir dari semangat tradisi pesantren dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad SAW dan konsensus (ijma’) para sahabatnya.
Buku karya Fauzan Alfas berjudul PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan terbitan PB PMII tahun 2015 menuturkan proses kelahiran PMII berikut karakter genealogi gerakannya. PMII dibentuk oleh 13 mahasiswa berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Menariknya, salah satu pendiri, Mahbub Djunaidi, sebelumnya aktif di HMI.
Awalnya, organisasi ini menjadi sayap kaderisasi NU di kampus. Namun, sejak 1972, PMII menyatakan independensinya, lepas dari bayang-bayang NU. Gerakan mereka selanjutnya terfokus pada realitas sosial rakyat bawah.
Bila HMI memiiki Nilai Dasar Perjuangan (NDP), PMII memiliki Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Pegangan kader-kader PMII tersebut menekankan pentingnya berpikir kritis, namun tetap membumi. Kaderisasi PMII tidak hanya soal nalar, tapi juga aksi nyata. Mereka akrab dengan demonstrasi, advokasi, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kader PMII kerap terlihat di desa-desa, lembaga advokasi, bahkan pendampingan tani dan buruh.
Dua Jalan Satu Tujuan
Di tengah perjalanan panjang bangsa Indonesia, organisasi kemahasiswaan memegang peran vital dalam membentuk arah berpikir dan kepemimpinan generasi muda. Di antara sekian banyak, HMI dan PMII tampil menonjol sebagai rumah besar pembinaan intelektual, kaderisasi kepemimpinan, serta medan perjuangan nilai keislaman dan kebangsaan.
Keduanya lahir dari semangat zaman yang berbeda. HMI pada tahun 1947, di tengah kobaran revolusi kemerdekaan, dan PMII pada tahun 1960, saat gelombang ideologi kiri mulai kuat merasuki ruang-ruang mahasiswa. Namun, keduanya mengemban amanat yang sama. Apalagi kalau bukan memperjuangkan kemajuan umat dan bangsa melalui cara yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing.
Sering kali HMI dan PMII dibandingkan, bahkan dipertentangkan. Tak jarang, semua itu berujung pada kontroversi yang tak perlu. Perbedaan keduanya adalah kekayaan demokrasi intelektual milik republik ini yang tak terbantahkan. Bila HMI membawa lentera pemikiran Islam modern dan rasional, PMII menjaga bara Islam tradisional yang berpihak pada rakyat kecil. Keduanya bak satu tubuh yang tak mungkin saling menyakiti. Bila salah satunya sakit, bagian tubuh lain pun terasa sakit.
Abdul Rozak dalam buku karyanya berjudul Membangun Keadaban Demokrasi: Belajar dari Gerakan Sosiokultural Cak Nur dan Gus Dur terbitan Azka Pustaka Pasaman Barat tahun 2024 menyajikan titik temu tradisionalisme Islam dan modernisme Islam dalam wajah post-tradisionalisme Islam dan post-modernisme Islam atau neo-modernisme Islam.
Penulis menjelaskan, neo-modernisme Islam mendialogkan Islam dan dunia modern, dengan tetap berpijak pada tradisi. Sementara post-modernisme Islam berangkat dari tradisi yang harus didialogkan dengan modernitas. Neo-modernisme cenderung berorientasi pada tataran makro-struktural, sedangkan post-tradisionalisme dekat dengan pemberdayaan masyarakat berikut gerakan emansipatorisnya.
Meski berbeda pada lingkup konseptual, orientasi, dan praksis gerakan, baik neo-modernisme maupun post-tradisionalisme tak lain sebentuk gerakan pembaruan pemikiran Islam dalam rangka menjadikan Islam sebagai agama Samawi yang fungsional dalam kehidupan umat manusia. Keduanya berusaha menembus batas-batas ketertutupan demi respons aktif atas zaman yang terus berubah.
Tampak jelas bahwa HMI yang cenderung neo-modernis dan PMII yang cenderung post-tradisionalis berpengaruh besar pada bentukan sosiokultural Indonesia. Terlebih, populasi umat Islam yang mayoritas di negeri ini adalah medan dakwah dan perjuangan nyata. Dari pergulatan gerakan inilah nilai-nilai kebangsaan terawat baik, serta tersimpul lestari. HMI dan PMII senyatanya saling melengkapi dengan kelebihannya masing-masing.
Lebih lanjut, baik HMI dan PMII mengusung prinsip ‘netral aktif’ dalam politik, meski praktiknya dipengaruhi sejarah masing-masing. HMI dengan spektrum lebih luas dan lintas partai, sedangkan PMII banyak beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NU. Namun, esensinya tetap sama. Keduanya bukan underbow partai, melainkan penyemai nilai-nilai kepemimpinan dan keumatan.
Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kemiskinan struktural, dan krisis moral, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin politik. Negara ini membutuhkan pemimpin ideologis yang tumbuh dari proses kaderisasi penuh kejujuran dan mendalam.
HMI dan PMII bukan sekadar organisasi. Keduanya ‘madrasah peradaban’. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan bahan untuk saling belajar dan memperkuat. Jika keduanya mampu merajut kerja sama lintas nilai maka umat Islam Indonesia akan memiliki fondasi peradaban yang kuat, mulai dari menara kampus maupun lorong-lorong kampung. Sedari kebijakan elite hingga manunggal dengan akar rumput.
HMI-PMII tak lain sebentuk potret rajutan persaudaraan demi pembangunan peradaban yang semakin baik. Setiap saat, diperlukan refleksi atas dinamika gerakan mahasiswa Islam dan semangat ukhuwah kebangsaan. Pernyataan Cak Imin tentang siapa yang ‘tumbuh dari bawah’, apakah HMI atau PMII, dapat dimaknai sebagai ruang refleksi atas dinamika yang ada. Semacam pertanyaan—bukan pernyataan—seputar, masihkah HMI dan PMII dekat dengan rakyat?
Editor: Arif Giyanto