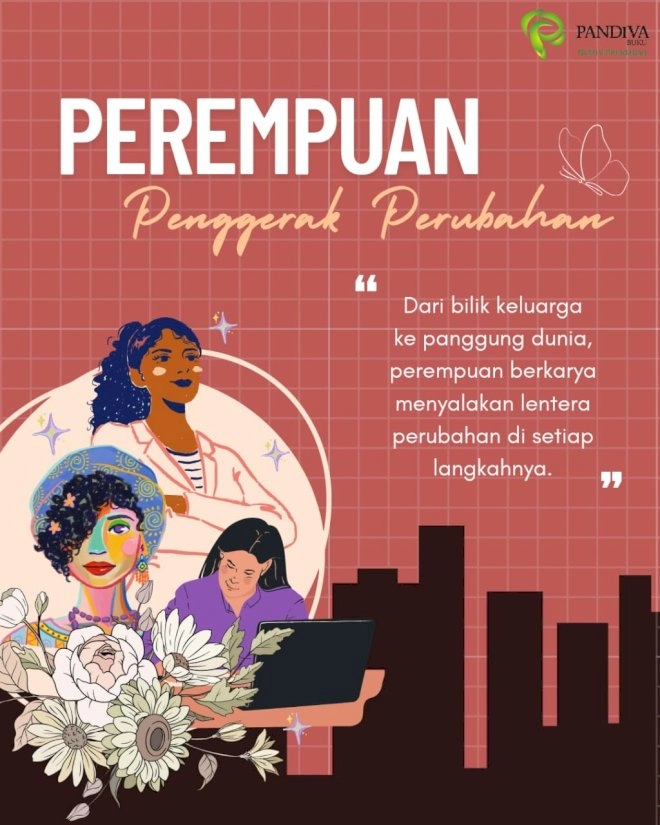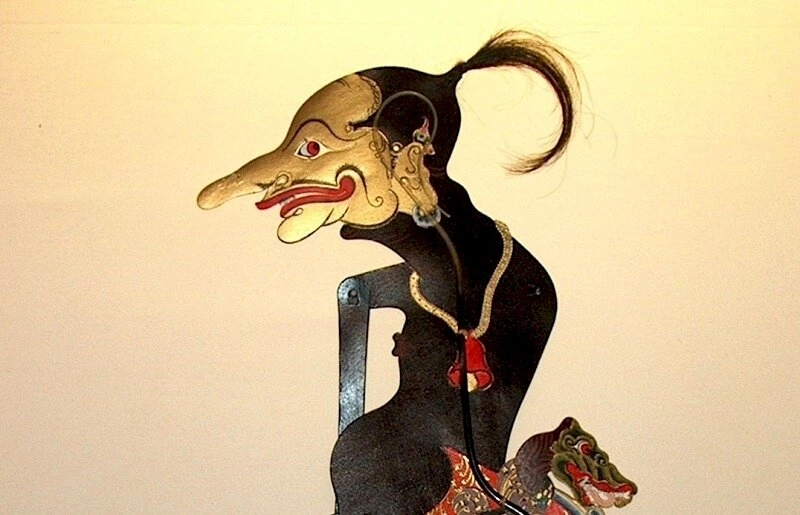Gerak Labuh Negara Arsipelago
/ Opini
Keberhasilan Indonesia di sektor kelautan sangat ditentukan oleh peran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Abimanyu Takdir Alamsyah
Guru Besar Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
Editor: Rahma Frida
Dalam sebuah seminar di Hanoi, saya menyampaikan konsep pengertian mengenai pulau dan kepulauan. Pulau bukanlah daratan kering di atas permukaan laut. Pulau adalah puncak dari struktur laut yang muncul di permukaan perairan atau lautan.
Beberapa waktu setelahnya, saya dihubungi perwakilan Hongkong dan Tiongkok. Mereka memohon izin untuk menerjemahkan paparan saya itu ke Bahasa Mandarin. Mereka juga mengundang saya bersama dua orang pakar dari Inggris untuk berdiskusi di Zhongshan University atau Sun Yat-sen University.
Pertemuan lanjutan digelar dalam format Seminar Kelautan di Qingdao, tepatnya Ocean University of China. Kali itu, saya turut dalam rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Seminar diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara.
Usai digelar beberapa diskusi tentang pulau dan kepulauan, lahirlah tiga pulau buatan di Laut Tiongkok Selatan serta diikuti oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah mereka.
Dengan pola serupa, kita dapat melihat jelas perkembangan perluasan Singapura pada tahun-tahun belakangan. Sementara Indonesia justru mengabaikan realitas ini serta tetap menggunakan definisi negara kontinental atau daratan.
Mirisnya, sebagian pengusaha Indonesia bahkan menjual pasir ke Negeri Singa, termasuk gerusan pulau-pulau perbatasan Kepulauan Riau. Beruntung, usai saya melakukan protes, Pulau Nipah masih bisa diselamatkan.
Istilah ‘arsipelago’ dalam Bahasa Indonesia berarti ‘Tanah Air’. Begitu bunyi klaim Indonesia di depan dunia internasional. Konvensi Hukum Laut Internasional, yakni UNCLOS 1982, menyempurnakan garis batas laut teritorial yang semula tercantum dalam Deklarasi Djuanda 1957.
Peningkatan positif lain adalah penambahan hak Indonesia untuk mengelola lautan seluas 200 mil laut di seluruh pulau perbatasan. Dengan demikian, luas hak pengelolaan lautan bagi negara arsipelago sangat berbeda dengan negara daratan kontinental yang berhenti hingga 12 mil laut.
Ada dua hal yang perlu segera dilakukan oleh negara arsipelago Indonesia. Pertama, penggambaran peta wilayah NKRI tidak lagi berbasis wilayah kepulauan, namun berbasis batas luar wilayah kelautan plus daratan yang bersebelahan dengan negara lain, di antaranya Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Kedua, pendidikan tentang Indonesia sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi perlu diubah, tidak seperti masa penjajahan yang kontinenal. Pendidikan harus berbasis negara arsipelago yang meliputi kehidupan di daratan kepulauan dan perairan kelautan Tanah Air Indonesia. Kesadaran ber-Tanah Air tidak bukan hanya sewaktu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, namun masuk ke dalam semua aspek kehidupan berbangsa.
Semua sektor ilmu pengetahuan mengenai Indonesia, mulai dari hukum, sosial, seni, budaya, ekonomi, kesehatan, hingga teknologi telah saatnya berbasis kearsipelagoan (Tanah Air), sehingga setiap warga negara, bahkan yang hendak menempuh studi ke negeri kontinental, dibekali kesadaran tersebut. Jangan sampai, saat mereka lulus dan kembali pulang, justru membawa pengaruh ilmu budaya daratan.
Sebagai negara arsipelago terbesar di dunia, Indonesia merupakan acuan utama bagi negara arsipelago yang lain sebagai basis hidup di daratan hingga lautan, sejak masa kini hingga kelak pada masa di mana sebagian wilayah daratan telah berubah menjadi wilayah lautan, akibat kenaikan muka laut.
Melihat perkembangan terkini, tambahan UNCLOS 1982 mengenai alur laut di dalam teritorial Indonesia perlu direvisi, karena ukuran kapal yang kian hari semakin besar, berikut dampak lingkungan yang merugikan saudara-saudara kita yang tinggal di lautan. Belum lagi, ekosistem laut yang terganggu, dan masih banyak lagi.
Menurut saya, alur laut cukup satu, yakni laut dalam, melewati Selat Makassar sebagai jalur lewat kapal internasional. Jalur itu lebih ketat daripada melewati Terusan Suez atau Terusan Panama, sekaligus gerbang masuk pelabuhan utama Indonesia di antara Balikpapan dan Samarinda, juga di pantai barat Sulawesi, salah satunya, Makassar.
Dengan kenaikan permukaan laut yang mempengaruhi wilayah pesisir, Indonesia perlu kembali menata jalur kemaritiman, termasuk peluang perkembangan global yang ada. Terusan Khatulistiwa yang menghubungkan lautan dan kepulauan timur Indonesia dengan ‘jalan tol’ ke Selat Makassar serta pembukaan pelabuhan-pelabuhan internasional di tepi timur Sumatera Utara dan Aceh dapat menambah gerbang interaksi laut perdagangan antara Indonesia dan dunia.
Semua penyiapan peran ini dapat dijadikan strategi pengembangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditakdirkan memiliki lautan nan luas dan strategis. Saya berharap, tidak ada lagi jalur laut yang justru memotong-motong NKRI.
Peran Vital KKP
Kiranya kurang arif bila Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkesan lebih berorientasi pada sektor perikanan. Sementara menurut saya, KKP bukan hanya mengurusi pangan atau tata niaga perikanan. Domain KKP juga bukan hanya tentang nelayan yang tinggal di pesisir dan lautan. Secara taktis-strategis, KKP dapat lebih berperan dalam memantapkan konsep negara arsipelago yang dapat ‘melihat’ kepulauan Indonesia dari dasar laut hingga ke puncak gunung.
Sejarah mencatat trik Malaysia yang sejak awal mengincar kekayaan laut Ambalat melalui klaim hak ‘memiliki’ Pulau Sipadan dan Ligitan, karena telah ‘memeliharanya’, sedangkan Indonesia belum juga terlalu peduli dengan pulau laut perbatasannya.
Terus terang saya sedih sewaktu beberapa kali diajak berdiskusi mengenai kondisi ketertinggalan Pulau Bitung Sulawesi Utara dan Mentawai Sumatera Barat yang termasuk daerah tertinggal Indonesia. Bagaimana mungkin, kepulauan perbatasan Indonesia yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan justru termasuk daerah tertinggal?
Setidaknya, satu dekade berlalu, identitas ‘Negara Kelautan’ pernah sangat memberi harapan bagi masa depan NKRI. Namun pada praktiknya, KKP lebih memprioritaskan aspek lainnya, seperti pertahanan laut dan perikanan.
Pun dengan perguruan tinggi. Saya khawatir, kampus yang menyiapkan masa depan keunggulan negeri di bidang kelautan tidak menyinggung permasalahan utama negara arsipelago atau negara kelautan Tanah Air kita selama ini. Terlebih apabila sumber daya manusia yang diberi kesempatan untuk belajar ke luar negeri hanya mengambil topik-topik ilmu pengetahuan yang sesuai negara tempat mereka belajar.
Terus terang, sewaktu memperoleh beasiswa lanjutan ke Cambrige University, saya menolaknya. Alih-alih studi tersebut berada dalam kerangka pendalaman ilmu yang bermanfaat bagi Tanah Air, kenyataannya hanya belajar rupaneka ‘kesalahan negara berkembang’ dalam membangun negaranya.
Eropa sendiri menunjukkan bukti bahwa sekian banyak suku bangsa yang tinggal bersama di satu daratan luas tidak bersatu, namun justru bersaing satu sama lain untuk memperoleh kepentingan masing-masing.
Indonesia beruntung memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun tinggal di banyak pulau dan wilayah lautan, namun kita masih mengutamakan persatuan, kecuali mungkin, kalangan yang hanya mementingkan Pulau Jawa.
*** Penulis adalah staf pengajar di Universitas Indonesia dengan latar belakang S1 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, S2 Kajian Pengembangan Perkotaan, serta S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia. Penulis pernah turut dalam pembinaan program Mitra Bahari di 34 Provinsi bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.