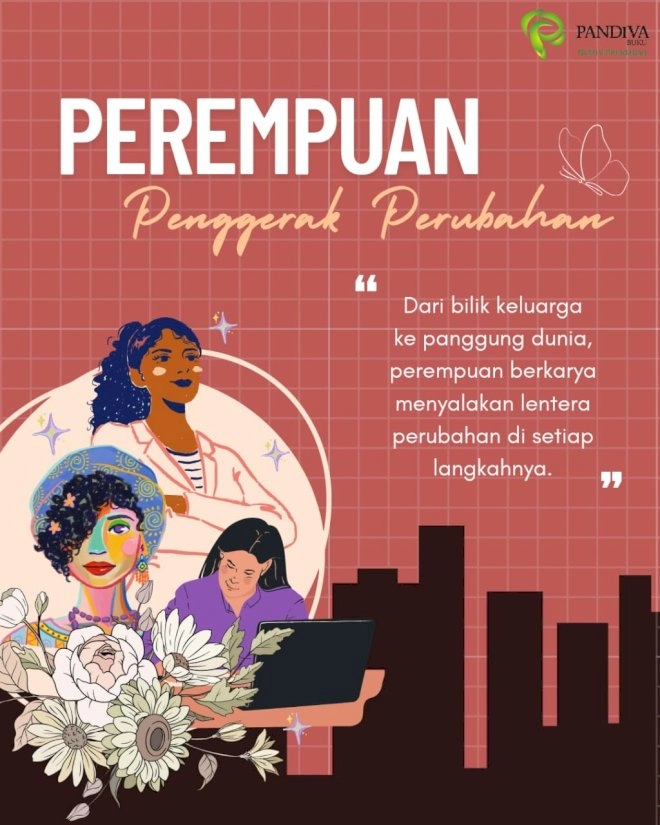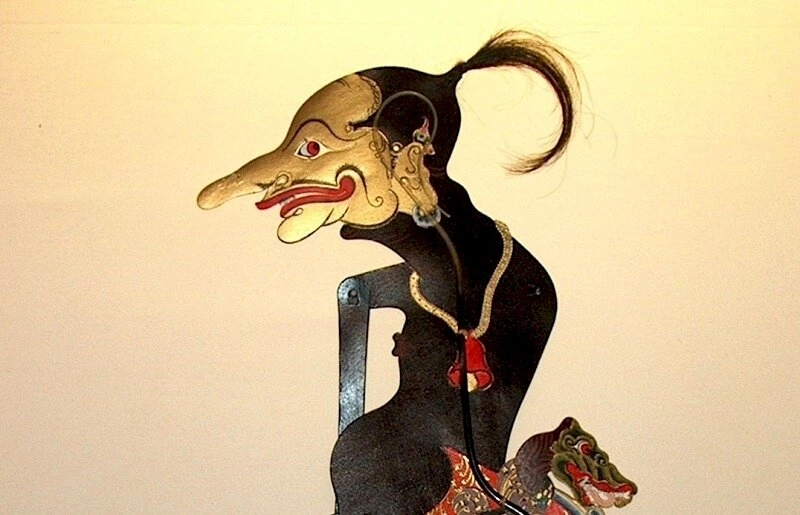Bagaimana Mungkin, Investasi Tinggi Tapi Jumlah Pengangguran Meningkat?
/ Opini
Iklim investasi yang kondusif dipercaya dapat menyelesaikan persoalan ekonomi riil, seperti pengangguran dan kemiskinan.
Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen FEB
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Akhir tahun 2024, sejumlah enam kabupaten dan kota di Jawa Tengah didapuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah mencapai realisasi investasi tertinggi.
Kabupaten Kendal pada peringkat pertama dengan realisasi investasi sebesar Rp10 triliun. Realisasi investasi kabupaten ini tertinggi di Jawa Tengah karena keberadaan Kawasan Industri Khusus (KIK) dengan proyek-proyek dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Kabupaten Boyolali menempati posisi kedua dengan angka realisasi investasi mencapai Rp9,7 triliun. Ketiga, Kota Semarang. Realisasi investasinya hingga Rp7 triliun. Posisinya sebagai ibu kota provinsi menjadikan kota ini menarik bagi investor di bidang jasa, perdagangan, dan properti.
Kabupaten Batang menjadi kabupaten dengan realisasi investasi terbesar keempat. Realisasi investasinya mencapai Rp6,39 triliun. Kabupaten Batang mempunyai keunggulan dalam iklim investasi, sebab adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang menjadi magnet bagi PMA maupun PMDN.
Selanjutnya, posisi kelima ditempati Kabupaten Jepara. Realisasi investasinya sebesar Rp4,5 triliun. Realisasi investasi tersebut datang oleh sektor padat karya, yaitu manufaktur furnitur dan garmen. Sektor industri manufaktur mereka didominasi oleh PMA.
Pada posisi keenam, tercatat Kabupaten Klaten. Realisasi investasi Klaten mencapai Rp3,5 triliun. Kabupaten Klaten menarik bagi investor dalam negeri atau PMDN, terutama di sektor industri manufaktur dan properti.
Pertanyaannya, apakah dengan menciptakan iklim investasi yang baik, sebuah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, bisa dikatakan berhasil melaksanakan program pembangunan ekonominya? Selain itu, sebuah kota disebut beriklim investasi yang baik, apakah diukur dari pengajuan izin investasi ataukah realisasi investasi?
Secara ideal, realisasi investasi mempunyai dua implikasi, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru yang bermuara pada pemberantasan kemiskinan. Faktanya, data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka pengangguran di provinsi ini pada bulan Februari tahun 2025 masih mencapai 4,33 persen atau 950.000 orang. Artinya, masih di atas batas psikologis 4 persen dari total angkatan kerja (lihat Todaro, 2005).
Jika ada banyak daerah dengan iklim investasi baik dan asumsinya mempunyai realisasi investasi baik maka seharusnya semakin banyak pula pekerjaan yang tercipta, sehingga jumlah penganggur semakin berkurang.
Pentingnya Kebijakan Riil
Iklim investasi yang kondusif bagi sebuah daerah memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan beberapa masalah ekonomi riil, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Dalam khazanah teori, ada dua pendapat utama tentang kebijakan ekonomi. Pendapat pertama menyatakan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah hanyalah menciptakan sebuah kondisi dalam perekonomian yang mempermudah terciptanya mekanisme pasar.
Pemerintah dalam hal ini hanya bertugas untuk menciptakan regulasi untuk menjamin terjadinya mekanisme pasar. Kelompok pertama percaya dengan teori liberalisme dalam pembangunan ekonomi atau sering juga disebut sebagai kelompok neo-klasik.
Kelompok kedua, yakni para ilmuwan ekonomi yang menyatakan bahwa peran pemerintah tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga harus melakukan campur tangan langsung dalam perekonomian. Campur tangan dalam perekonomian diperlukan untuk menjaga agar para pelaku ekonomi tidak menggunakan asas oportunitas atau mencari keuntungan dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Williamson dan Ouchi (1980) yang menulis tentang teori transaction cost menyatakan bahwa individu atau manusia mempunyai dua keterbatasan, yaitu rasionalitas terbatas (bounded rationality) dan perilaku mencari kesempatan (opportunism behavior). Teori tersebut menjadi salah satu dasar dari kontrol atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
Krisis ekonomi keuangan yang melanda Amerika Serikat dan Eropa serta hingga kini masih terasa dampaknya diakibatkan oleh perilaku mencari kesempatan oleh pelaku ekonomi. Para investor dengan dana besar lebih banyak berinvestasi di sektor keuangan dengan instrumen derivatif yang lebih menguntungkan daripada berinvestasi di sektor manufaktur.
Padat Modal Versus Padat Karya
Pada level kebijakan ekonomi di daerah, pemerintah daerah sudah berupaya untuk menentukan kebijakan industri yang tepat. Hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah sudah melakukan studi untuk menentukan komoditas unggulan berikut analisis daya saing bagi masing-masing industri. Meski begitu, pada tahap pelaksanaan, muncul banyak masalah terkait dengan koordinasi antar-lembaga pemerintah daerah maupun antar-daerah.
Faktanya, sektor industri sekarang semakin berkembang ke arah industri padat modal daripada industri padat karya. Industri padat modal lebih berisiko minimal dengan keuntungan yang tinggi. Artinya, para pelaku ekonomi (baca: investor) lebih mengutamakan investasinya pada industri-industri padat modal. Industri padat modal pada praktiknya tidak menyelesaikan masalah ekonomi riil yang dihadapi sebagian besar daerah di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran.
Realisasi investasi yang masuk ke beberapa daerah di Indonesia mengembangkan sektor jasa, keuangan, dan perdagangan. Sektor manufaktur yang masuk kebanyakan adalah sektor manufaktur padat teknologi.
Jenis-jenis industri itu tidak memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga perannya terhadap masalah pengangguran dan kemiskinan, kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan penentuan prioritas, industri apa yang akan dikembangkan.
Belum Berdampak Nyata
Berdasarkan data realisasi investasi yang mengalami peningkatan di Jawa Tengah pada tahun 2024, seharusnya berdampak pada pembukaan lapangan kerja pada sektor formal. Sayangnya, tidak demikian di Jawa Tengah.
Pada bulan Agustus 2024, jumlah orang yang bekerja di Jawa Tengah sejumlah 20,86 juta orang. Memasuki Februari 2025, angka ini meningkat menjadi 20,92 juta orang. Jumlah orang yang bekerja bertambah sebanyak 600.000 orang.
Berdasarkan data ini, kita tentu menduga bahwa realisasi investasi berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Namun demikian, jika kita dalami detail dari data tersebut ternyata dari 20,86 juta orang yang bekerja pada bulan Agustus 2024, sebanyak 12,44 juta orang atau 59,64 persen bekerja di sektor informal dan 8,42 juta orang atau 40,36 persen bekerja di sektor formal.
Pada bulan Februari 2025, jumlah orang yang bekerja di Jawa Tengah mencapai 20,92 juta orang dengan rincian 12,65 juta orang atau 60,45 persen berkerja di sektor informal dan hanya 8,28 juta orang atau 39,55 persen bekerja di sektor formal.
Dari bulan Agustus 2024 sampai Februari 2025 terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di sektor informal sebanyak 210.000 orang. Sementara jumlah orang yang bekerja di sektor formal justru mengalami penurunan sebanyak 140.000 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di Jawa Tengah belum berdampak pada pembukaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Tambahan jumlah orang yang bekerja pada bulan Februari 2025 berasal dari sektor informal yang menghasilkan pekerjaan dengan upah dibawah upah minimum dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan.
Kesimpulannya, predikat ‘ramah investasi’ saja tak cukup. Pemerintah daerah perlu menjelaskan pada investor tentang risiko dan keuntungan yang muncul dari sektor ekonomi unggulan di daerahnya.
Selain itu, berdasarkan analisis dan studi produk dan komoditas unggulan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan industri apa yang layak dikembangkan. Pilihannya, industri yang mempunyai daya saing tinggi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hanya dengan kebijakan industri inilah maka keputusan untuk membangun iklim investasi kondusif di daerah bisa menyelesaikan masalah ekonomi riil di daerah, yaitu pengangguran dan kemiskinan.
Editor: Rahma Frida