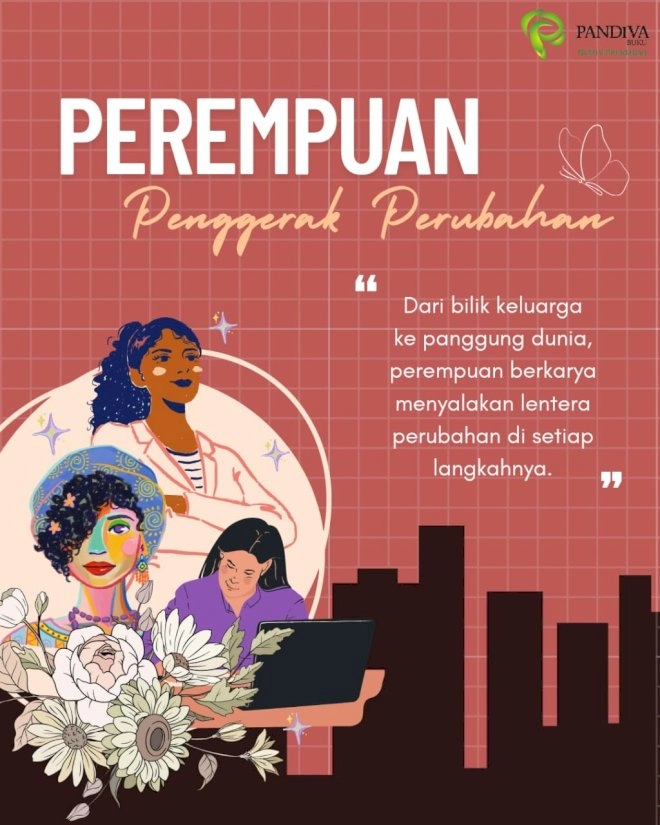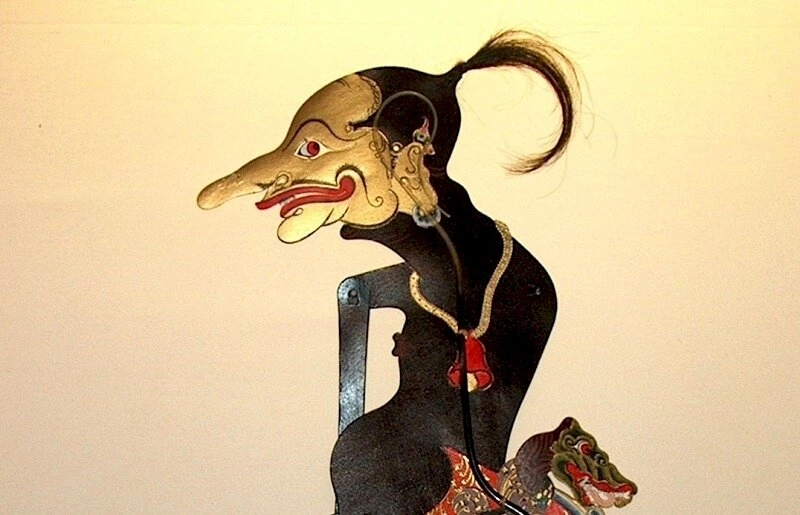‘Ridho Effect’ Berkemajuan
/ Inspirasi
Keberhasilan Rizky Ridho dalam menyejajarkan kualitas diri adalah inspirasi penting.
Arif Giyanto
Chairman Pandiva. Penulis buku Kelas Menengah Progresif.
Rasanya, saya sulit melupakan momentum itu. Minggu, 21 Oktober 2001, saya menghadiri Temu Nasional Mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang digelar di Bandung, tepatnya Universitas Islam Bandung (UNISBA). Salah satu rekomendasi monumental forum tersebut, yakni lahirnya Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia (IMEPI).
Kehadiran saya mewakili Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (HIMEPA FE UMS). Saya adalah Ketua Umum HIMEPA FE UMS Periode 2001-2002. Sebelumnya, HIMEPA FE UMS bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (HMJ-IESP).
Sewaktu menjabat Ketua Umum HIMEPA FE UMS, saya baru saja menapaki masa kuliah Semester V dan usia saya, persis dua dekade. Artinya, energi aktivisme kemahasiswaan saya tengah pada puncak-puncaknya. Terma-terma ideologis seperti kapitalisme global, ekonomi kerakyatan, hingga keadilan sosial meresap perlahan ke dalam sanubari saya.
Intelektualisme saya begitu membara. Dalam rentang sekian semester, saya telah mengunyah lusinan referensi tentang karut-marut perekonomian nasional. Saya kesengsem pada pemikiran Sritua Arief, seorang neo-strukturalis kebanggaan UMS. Kepercayaan diri saya sebagai seorang ekonom nasional usia mahasiswa menebal kuat.
Temu nasional resmi dibuka. Tahapan diskusi digelar maraton. Sebagian tema diskusi menghadirkan pakar-pakar ekonomi. Sebagian tema lain dipimpin beberapa peserta yang dianggap mumpuni, salah satunya perwakilan Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya. Setelah lebih dua dekade, Berly kini Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Dalam setiap sesi, saya terlibat aktif. Saya mendengar, mencatat, bertanya, serta memberikan respons dan berdialektika. Sekali dua kali, saya masih dapat berkontribusi. Lama kelamaan, saya surut juga. Saya lebih banyak terdiam. Pembahasan mulai mengemuka detail dan banyak isu yang tak saya pahami.
Saya menatap ke sekeliling. Peserta forum yang aktif hanya segelintir. Mereka mulai tampak dominan. Segelintir mahasiswa pintar yang dominan tersebut berasal dari kampus-kampus ternama, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, hingga Universitas Brawijaya.
Diskusi maraton tersebut lantas bermuara pada rekomendasi strategis, baik teruntuk internal maupun eksternal, termasuk pemerintah. Saya masih saja kelu, tak mampu berurun rembuk, hingga forum berakhir dengan butir-butir gagasan penting yang selanjutnya dianggap sebagai agenda nasional.
Siapa sangka, kronik temu nasional di Bandung itu ternyata berlanjut dalam kehidupan saya pasca-lulus UMS. Setiap kali berurusan dengan hal-hal strategis berskala luas, sosok-sosok penting yang didapuk memiliki otoritas tak lain adalah alumnus perguruan tinggi ternama di Indonesia. Bila pun sedikit berbeda, personel yang ditambahkan atau dikolaborasikan ternyata justru lulusan kampus-kampus ternama luar negeri.
Ridho Effect
Pada sisi kehidupan lain, sejarah ditorehkan Rizky Ridho Ramadhani. Bersama tim nasional sepakbola, ia tengah berjuang sepenuh hati agar Indonesia lolos ke pentas paling bergengsi sejagat, Piala Dunia 2026. Berposisi sebagai bek, Ridho dan kawan-kawan masih harus melewati fase-fase kritis yang mensyaratkan kerja keras.
Ridho menjadi fenomenal bukan hanya karena kemampuannya bermain sepakbola. Ia satu-satunya pemain hasil binaan manajemen dalam negeri yang terhitung paling konsisten menjadi starter pilihan pelatih. Seperti diketahui, program naturalisasi pemain begitu masif pada periode kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Berlimpahnya para pemain hasil didikan Eropa dalam skuad Timnas tentu saja memunculkan kekhawatiran besar seputar kecilnya kesempatan para pemain didikan manajemen sepakbola dalam negeri. Dalam beberapa pertandingan terakhir, praktis Timnas bahkan didominasi para pemain didikan Eropa.
Sebenarnya, ada rekan sejawat Ridho, Marselino Ferdinan. Namun, meski pernah sama-sama merumput di kompetisi nasional, Lino kini berkarier di Eropa. Ridho jelas terasa lebih kental khazanah sepakbola dalam negerinya, karena ia bermain untuk Persija Jakarta yang turut dalam Liga 1.
Integritas Ridho dalam bermain sepakbola dihormati rekan-rekannya di Timnas. Dengan semua yang ia punya sekarang, beberapa kawannya di Timnas yang bermain untuk klub-klub Eropa menilai Ridho layak bermain bersama mereka. Ridho tak hanya mahir di dalam lapangan. Ia sosok supel nan terbuka saat di luar lapangan.
Capaian Ridho sekarang bukan hasil rekayasa artifisial. Setapak demi setapak ia lakoni perjalanan hidup dan kariernya sebagai sepakbola yang penuh liku. Ridho juga bukan anak yang lahir dari keluarga berkecukupan. Ia punya kisah sendiri tentang bertahan hidup sekaligus terus menyalakan tekadnya menjadi pesepakbola profesional.
Ketika harus bersaing, Ridho memosisikan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sewaktu dinomor-duakan, ia tetap sungguh-sungguh berlatih. Saat diberi kesempatan, ia menjawabnya dengan penuh tekad dan kepercayaan diri tinggi. Ridho sama sekali tidak rendah diri bersanding dengan rekan-rekan lain yang sarat khazanah sepakbola Eropa.
Ridho adalah potret kesungguhan dan indahnya rasa bersyukur. Ia tak pernah menyerah, meski keadaan tidak selalu nyaman. Tak lupa, ia seorang yang pandai bersyukur, ketika prestasi berada dalam genggamannya. Perilaku positif yang berhasil menginspirasi rekan-rekan pesepakbola dalam negeri lain, pun para generasi muda. Saya menyebutnya, ‘Ridho Effect’.
Bagi saya, ‘Ridho Effect’ dapat saya rasakan sangat kuat saat Timnas Indonesia U-17 berhasil lolos ke Piala Dunia. Meski harus terhenti pada tahap Delapan Besar Piala Asia U-17, permainan impresif yang penuh kebanggaan terpancar kuat dari para pemain. Dalam usia yang masih sangat muda, mereka seperti berhasil mengirim pesan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mendunia.
Siapa yang mengira, tak sedikit dari para pemain Timnas U-17 tersebut, lahir dan dibesarkan dalam kondisi berkekurangan. Kondisi yang tak lantas membuat mereka tertunduk dan menyalahkan takdir. Mereka berjuang dan berhasil. Bila pun belum berhasil, mereka bangga karena telah memilih untuk berjuang. Sebuah semangat generasi muda yang pantas digelorakan demi Indonesia yang lebih baik.
Berlomba dalam Kebaikan
Persaingan antar-manusia setua usia manusia itu sendiri. Persaingan yang niscaya tersebut pada praktiknya direspons bermacam oleh manusia, tergantung sudut pandang dan kepahaman masing-masing.
Pada satu sisi, persaingan dapat terasa mengerikan, karena hanya berujung pada menang-kalah. Sementara di sisi lain, persaingan dalam kebaikan justru diperlukan demi kualitas diri yang semakin baik. Setidaknya, persaingan dimaklumi sebagai hal wajar, asalkan dilakukan dengan penuh kejujuran dan jauh dari curang, apalagi iri-dengki.
Keberhasilan Rizky Ridho dalam menyejajarkan kualitas diri dengan rekan-rekan hasil didikan Eropa adalah inspirasi tentang pentingnya kesungguhan dan doa dalam setiap upaya, meski di tengah keterbatasan. Ia berlomba dalam kebaikan.
Berkelindan dengan reputasi Ridho yang luar biasa, ia adalah mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya). Berhasil masuk melalui jalur beasiswa atlet, Ridho mendaftar pada November 2022, jauh waktu sebelum ia membela Timnas menuju Piala Dunia 2026.
Gemblengan pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah tampak linier dengan dinamika perjalanan karier sepakbola Ridho. Sadar dengan segala keterbatasan berarti sadar pula dengan segala keunggulan. Bila tak unggul pada satu hal, keunggulan lain pasti didapatkan. Dengan begitu, hasil didikan Muhammadiyah telah sepatutnya tak gentar dalam persaingan apa pun, asalkan perihal kebaikan. Berlomba dalam kebaikan.
Februari 2020, saya diundang sebagai salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ekonomi maritim di Kota Yogyakarta. Saya tidak mengenal para penyelenggaranya. Menurut keterangan singkat, nama saya direkomendasikan oleh seseorang. FGD mengulas visi ‘poros maritim dunia’ dan dihadiri oleh pakar-pakar kompeten asal beberapa kampus ternama.
Tertera jelas nama saya pada map yang diberikan penyelenggara, lengkap dengan titel ‘Doktor’. Ketika diperkenalkan, moderator menyebut saya sebagai alumnus UGM dan banyak menulis tentang isu-isu kemaritiman. Hadirin sumringah. Mereka mungkin merasa beruntung, mendapatkan sosok yang tepat mengkaji tema suguhan penyelenggara.
Tibalah waktu saya berbicara. Sebelum menyampaikan pandangan dan rekomendasi seputar visi negara maritim, saya merasa perlu untuk memperjelas identitas diri saya. Saya berucap dengan intonasi bersemangat dan penuh keakraban.
“Bapak-Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Senang rasanya dapat berkumpul dan belajar bersama sosok-sosok kompeten yang ahli di bidangnya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya belum Doktor. Saya juga bukan alumnus UGM seperti yang disampaikan moderator. Saya alumnus Universitas Muhammadiyah Surakarta.”
Tampak sebagian mimik audiens terkaget-kaget. Namun, lebih banyak lagi yang terlihat lega. Mungkin lantaran wajah saya yang masih sangat asing di kalangan pakar kemaritiman. Mungkin juga karena intensi opini pembanding yang bisa jadi berbeda dari arus-besar. Ya, mereka membutuhkannya.
Saya sungguh sadar, siapa saya, dan sebisa apa saya berkontribusi. Namun, demi berlomba dalam kebaikan, saya yakin, setiap orang berkesempatan untuk memberikan persembahan terbaik. Jadi, teruslah berjuang dan berlomba dalam kebaikan, siapa pun Anda dan lulusan mana pun Anda.
Editor: Astama Izqi Winata